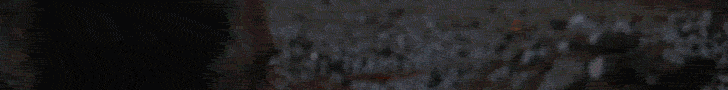Hamka (Haji Malik Karim Amrullah) naik kapal Kota Baru, yang bertolak dari Tanjung Priok tanggal 16 Agustus 1950, persis satu hari sebelum Hari Proklamasi. Ia ditunjuk oleh MPH (Majelis Pimpinan Haji) sebagai pemimpin jamaah haji di kapal tersebut, sebanyak 970 orang.
Dalam kapal lain berangkat sekitar massa yang sama, masing-masing dengan pemimpinnya. Hamka di dibantu oleh Asa Safagih dan Ayah Hamid sebagai anggota pimpinan. Ketua Panitia Haji Sumatera adalah H Bustami Ibrahim, yang sudah lama dikenalnya sebagai salah seorang pemimpin cabang Muhammadiyah di Medan.

Tahun 1950 adalah tahun kemerdekaan yang diakui di tengah bangsa-bangsa di dunia. Juga tahun pertama urusan haji dipegang oleh Pemerintah RI.” Tentu belum sempurna”, tulis Hamka, tetapi tidak lagi bergantung pada kebijakan pemerintah kolonial. Momen yang istimewa ini disertai kebanggan sudah berhasil berebut kemerdekaan, sudah mempunyai martabat orang Republikan, mewarnai seluruh kisah perjalanan ini. Catatan Hamka ini dirangkum dalam buku ‘Naik Haji di Masa Silam’, karya Henri Chambret-Loir.
Orang Belanda pun bersikap baru. Di atas kapal tanggal 17 Agustus, kapten kapal, seorang Belanda yang telah empat belas kali melakukan perjalanan pulang pergi antara Indonesia dan Saudi Arabia, mengucapkan sebuah pidato nasionalis yang menyanjung tinggi kemerdekaan Indonesia.
Saat merenungkan acara wukuf, Hamka membahas tema-tema yang lazim ditemukan dalam buku-buku lain (wukuf menyerupaki konggres Islam sedunia, pakaian ihram pakaian kebersamaan dengan kain kafan) serta juga tema terbaru: bangsa-bangsa di dunia bersifat sementara dan tergantung keadaan:”Tidak ada kebangsaan! Kebangsaan hanya istilah dalam hidup, menunggu perhitungan zaman dan tempat.” Indonesia dulu terbagi atas sekian kerajaan, sekarang bersatu dalam sebuah negara, tetapi untuk berapa lama?” “Akankah tetap begitu?” Ini pernyataan yang sangat berani, apalagi tahun 1950.
Salah satu keputusan pemerintah RI untuk membatasi jumlah jamaah haji dengan alasan negara kekurangan devisa, keputusan ini dikecam Hamka. ”Apa artinya harta benda, atau kekayaan nasional yang tertumpah ke luar, kalau sekiranya yang dicari ke mari itu adalah keteguhan jiwa? Yang menghisap kekayaan nasional bukanlah orang naik haji yang hanya sekali sekurangnya seumur hidup. Yang menghisap kekayaan nasional adalah kemewahan yang tidak berfaedah, yang ditimbulkan menurut dasar ilmu teknologi, sehingga yang tidak perlu menjadi sangat perlu, dan yang amat perlu sudah tidak perlu lagi.”

Renungan tentang hewan kurban juga terperngaruh oleh pengalaman yang masih segar dalam ingatan tentang berbagai kekerasan yang terjadi selama perang kemerdekaan: setelah merenungkan nasib manusia di dunia (di mana agama Islam membalas teori Marx dan Schopenhauer) timbulah gagasan bahwa penyembelihan hewan kurban perlu agar manusia membiasakan diri dengan darah, karena darah diperlukan oleh kemajuan: kemerdekaan tidak akan tercapai kalau tidak ada darah tertumpah!
Hamka bersikap sangat kritis terhadap pemerintah Arab Saudi. Kalau kita mengingat sikapnya selama 23 tahun sebelumnya (Hamka pertama pergi haji pada tahun 1927), ketika ia naik haji sebagai pemuda yang mengagumi pemerintahan Ibu Saud yang baru menguasai Tanah Arab, kita patut bertanya mengapa tanggapannya begitu berbeda. Ini barangkali disebabkan peristiwa di bidang politik atau keagaman yang tidak disinggung di sini.
Pada kesempatan perjamuan di Istana tanggal 8 Dzulhizah Hamka melukiskan acara makan itu dengan ironi tajam, apalagi amat kritis terhadap puji-pujian kelewat muluk yang dialamatkan oleh beberapa pujangga kepada Raja Abdulaziz. Katanya, ini tidak sesuai dengan adat dan sejarah kita. Tulisnya: ”tanah kita tidak tanah fedolal.”
Di bagian akhir buku ia kembali meninjau keadaan Arab Saudi yang mendadak kaya dengan minyak, tetapi kekayaan ini digunakan golongan pemimpin untuk kesenangan sendiri, sedangkan rakyat dibiarkan melarat.
Di atas kapal, Hamka mengaku menghadai banyak masalah tingat pendidian para jamaah yang umumnya rendah. Kebanyakan jamaah adalah orang dusun yang tidak mempunyai kesadaran kesehatan dan tidak mengindahkan aturan apa pun. Kalaupun dipasang rambu, tidak dibaca. Kalau dibaca, tidak dimengerti. Ada yang membuang air di mana-mana, ada yang merokok di palka, ada laki-laki mandi telanjang di kamar mandi wanita: Mereka tidak mengenal disiplin, hanya tunduk kepada perintah dan kekuasaan.

Pada saat itu Hamka juga mengamati kepolosan sementara jamaah haji yang naif dan mudah ditipu dan tidak mampu membedakan takhayul dan akidah. Pengamatan jenis ini biasanya disertai rasa kasihan bila kepolosan mereka dimanfaatkan orang lain, tetapi kesimpulan Hamka lebih jauh: mereka sebenarnya tidak memenuhi syarat-syarat haji: ”kalau diperiksa betul hikmat haji, sudah terang bahwa sebagian besar belum wajib haji.”
Pada masa itu, kondisi wilayah Arafah, Mina, dan Mudzalifah saat puncak haji sudah terjadi kemacetan yang parah. Jarak tiga kilometer antara Mudzalifah dan Mina saat itu sudah memerlukan satu jam perjalanan.